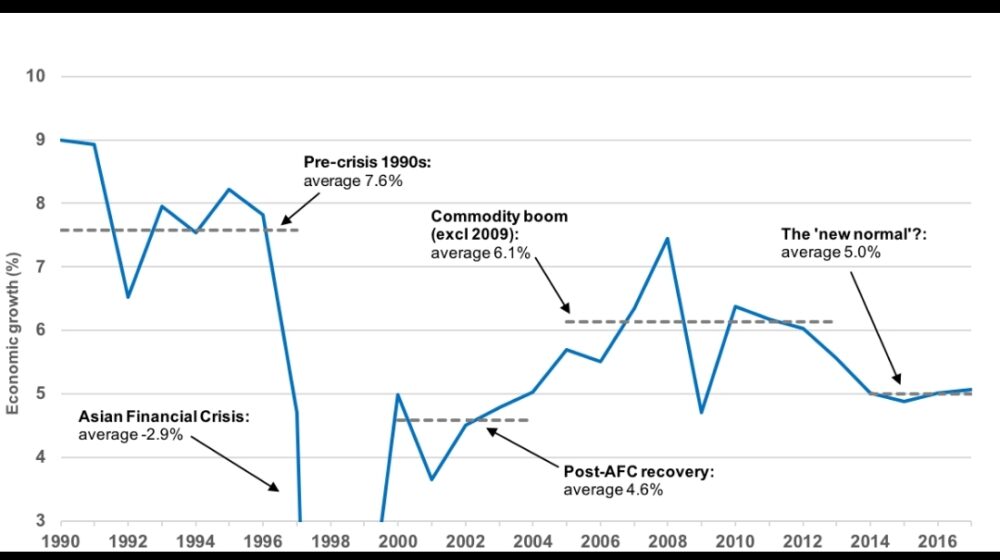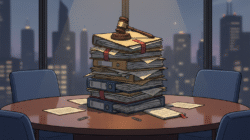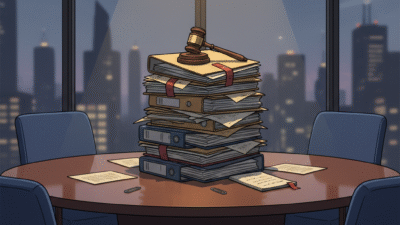Jakarta, mediahukumnews.com – Meski angka pengangguran terbuka nasional untuk Februari 2025 tercatat 4,76 persen, menurun dari 4,82 persen dari tahun sebelumnya, angka ini menyembunyikan fakta bahwa jumlah pengangguran masih belum benar-benar turun. Yaitu bahkan menjadi 7,28 juta orang dibandingkan 7,20 juta orang tahun lalu.
Sementara itu, upah rata-rata pekerja pada Februari 2025 hanya 3,09 juta rupiah per bulan, hanya naik 1,78 persen dibanding Februari 2024. Dalam kondisi demikian, masyarakat menghadapi penghasilan yang stagnan, bersamaan dengan kebutuhan hidup yang terus naik. Ini justru malah memunculkan ketegangan sosial yang kian nyata.
Di sisi inflasi, angka juga mencatat dinamika yang tidak biasa. Indeks harga konsumen (CPI) Indonesia pada Maret 2025 tercatat inflasi 1,03 persen Year over Year (yoy), atau 1,65 persen Mark to Market (mtm), jauh di bawah target koridor inflasi pemerintah yaitu 2,5 persen dengan rentang kurang lebih 1 persen ke atas dan ke bawah, yaitu di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Sementara memang terdengar baik, namun kondisi ini bukan semata stabilitas ekonomi. Diskon listrik 50 persen dan kebijakan serupa, turut memicu deflasi di beberapa komponen. Artinya, daya beli masyarakat sesungguhnya belum pulih secara signifikan. Bahkan, tekanan ke bawah pada harga menunjukkan permintaan domestik yang lemah.
Kondisi ekonomi yang tampak tenang secara makro ini, lalu menjadi latar belakang munculnya gejolak sosial. Para analis menyebut, bahwa meski tingkat pengangguran persentasenya turun, partisipasi angkatan kerja naik, sehingga justru jumlah pekerja yang terserap tak sebanding bertambahnya pencari kerja. Yang berarti keterserapan tenaga kerja rendah. Kredit bank nasional pun tumbuh melambat, yakni hanya 8,88 persen yoy hingga April 2025. Ini menandakan pelambatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Kombinasi stagnasi upah, minimnya peluang kerja formal, dan tekanan ekonomi inilah yang memantik demonstrasi publik dan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
Persoalannya kini bukan sekadar angka, melainkan pertanyaan struktural. Apakah pemerintah akan memetakan ulang prioritas kebijakan untuk memperkuat daya beli, menciptakan pekerjaan layak, dan membangun kembali kepercayaan publik, atau memilih jalur konsolidasi kontrol yang semakin menutup ruang kritik sosial? Gelombang ketidakpuasan yang menggeliat, menunjukkan bahwa titik‐jenuh sudah hampir tercapai. Jika ekonomi rakyat kecil terus terabaikan, maka gejolak sosial ini bisa menjadi pemantik fase pergeseran kekuasaan, yang tak hanya mempertanyakan ‘siapa yang memimpin’, tetapi ‘untuk siapa kekuasaan dijalankan’. ***