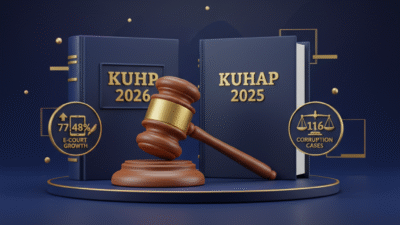Jakarta, mediahukumnews.com – PEMBERLAKUAN Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan mendasar wajah hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya, hukum pidana nasional secara eksplisit membuka ruang penerapan “hukum yang hidup dalam masyarakat” (living law) sebagai dasar pemidanaan. Di satu sisi, ketentuan ini dipuji sebagai pengakuan atas nilai lokal dan kearifan adat. Namun di sisi lain, pasal ini memicu kekhawatiran serius yaitu ketika hukum tidak lagi sepenuhnya tertulis, sejauh mana kepastian hukum masih bisa dijaga?
Dalam praktik hukum pidana lama (KUHP warisan kolonial), asas legalitas diterapkan secara ketat melalui prinsip nullum delictum nulla poena sine lege (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis). Hukum adat hanya berperan terbatas, terutama dalam konteks sanksi sosial atau hukum perdata adat. Penegakan pidana sepenuhnya bergantung pada rumusan pasal tertulis, sehingga ruang subjektivitas aparat relatif sempit. KUHP baru menggeser paradigma ini dengan memberi legitimasi pidana pada norma yang hidup, namun tidak selalu terdokumentasi secara formal.
Mahkamah Konstitusi, sejatinya telah lama menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai hak konstitusional warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan MK terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam beberapa putusan pengujian undang-undang pidana, MK konsisten menyatakan bahwa norma pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar tidak membuka peluang kesewenang-wenangan aparat. Di titik inilah Pasal 1 ayat (2) KUHP diuji secara konstitusional dalam praktik, apakah penerapan “living law” dapat tetap tunduk pada standar kepastian hukum yang selama ini dijaga MK.
Masalah utama bukan pada pengakuan hukum adat itu sendiri, melainkan pada siapa yang menafsirkan dan bagaimana standar pembuktiannya. Tanpa pedoman nasional yang ketat, aparat penegak hukum berpotensi menjadi penafsir tunggal atas nilai sosial suatu komunitas. Situasi ini membuka risiko kriminalisasi selektif, ketimpangan penegakan antar daerah, dan pelemahan kontrol yudisial. Jika praktik lama menempatkan undang-undang sebagai pagar kekuasaan, maka praktik baru berisiko mengendurkan pagar tersebut.
Pasal “living law” dalam KUHP baru adalah pertaruhan besar reformasi hukum pidana Indonesia. Ia bisa menjadi jembatan antara hukum negara dan rasa keadilan masyarakat, atau sebaliknya menjadi celah bagi subjektivitas aparat yang menggerus kepastian hukum. Konsistensi dengan prinsip-prinsip yang selama ini ditegakkan Mahkamah Konstitusi menjadi kunci. Tanpa pengawasan yudisial dan pedoman implementasi yang ketat, hukum pidana berisiko kehilangan wataknya sebagai pelindung warga negara. ***